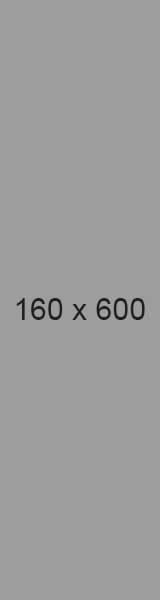
Oleh Muhamad Fadhil, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Malang
Bicara tentang komunikasi lingkungan khususnya di Indonesia, tidak pernah lepas dari tarik menarik kekuasaan, budaya, ekonomi, dan media. Isu-isu seperti deforestasi, krisis air, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), food estate, hingga tambang nikel sering kali dikomunikasikan bukan berdasarkan urgensi ekologis, melainkan melalui sudut pandang ekonomi-politik yang dikendalikan oleh aktor-aktor dominan seperti negara dan korporasi. Dalam hal ini, deforestasi menjadi salah satu isu paling mencolok, karena meskipun secara global dianggap sebagai salah satu penyebab utama perubahan iklim, di Indonesia justru sering dijadikan alat untuk kepentingan ekonomi jangka pendek.
Pemerintah Indonesia, misalnya, terus mendorong kebijakan ekspansi lahan untuk industri sawit, pertambangan, serta proyek-proyek infrastruktur besar seperti pembangunan IKN, yang kerap melibatkan pembukaan hutan yang luas. Walaupun ada berbagai upaya yang diklaim oleh pemerintah untuk mengurangi laju deforestasi, seperti moratorium izin baru untuk kawasan hutan dan peningkatan penggunaan energi terbarukan, kebijakan-kebijakan ini sering kali terhambat oleh konflik kepentingan antara pembangunan ekonomi dan konservasi alam. Hal ini semakin diperparah dengan lemahnya pengawasan terhadap praktik-praktik illegal logging dan kebakaran hutan yang sering terjadi, yang masih menjadi ancaman serius terhadap ekosistem hutan tropis Indonesia.
Deforestasi malah seringkali disajikan dalam narasi yang lebih mengutamakan potensi ekonomi, seperti investasi dan lapangan pekerjaan, daripada mempertimbangkan kerusakan ekologis jangka panjang. Program-program seperti food estate, yang mengalihkan lahan hutan untuk pertanian skala besar, sering dibungkus dengan wacana kedaulatan pangan dan penciptaan lapangan kerja, meskipun dampaknya terhadap kerusakan habitat alami dan perubahan iklim sangat signifikan. Media sering kali memfasilitasi narasi ini, sementara dampak buruk terhadap masyarakat lokal dan hilangnya keanekaragaman hayati justru diabaikan.
Di sisi lain, korporasi yang terlibat dalam eksploitasi sumber daya alam juga memiliki pengaruh besar dalam membentuk narasi lingkungan. Dalam banyak kasus, mereka memanfaatkan hubungan dekat dengan pemerintah untuk memperjuangkan kepentingan ekonomi mereka, sekaligus berusaha mengalihkan perhatian publik dari praktik merusak yang mereka lakukan. Salah satu contohnya adalah pengolahan sawit yang sering kali mengorbankan hutan hujan tropis yang merupakan habitat berbagai spesies langka dan sumber daya alam yang tak ternilai.
Situasi ini menyoroti bagaimana komunikasi lingkungan di Indonesia sering terdistorsi oleh kepentingan politik dan ekonomi, mengorbankan kelestarian alam untuk keuntungan jangka pendek. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk lebih kritis dalam memahami bagaimana narasi-narasi ini dibentuk dan disebarkan, serta mendorong perubahan menuju komunikasi yang lebih transparan dan berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang. Mencakup hal ini, teori konstruksi sosial dari Peter L. Berger dan Thomas Luckmann (1966) sangat relevan untuk memahami bagaimana realitas lingkungan dibentuk secara sosial dan politis.
Menurut Berger dan Luckmann, realitas sosial dibentuk melalui tiga tahapan: eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Ketiga proses ini terjadi pula dalam komunikasi lingkungan di Indonesia:
Eksternalisasi
Pada tahap ini, individu atau institusi menciptakan makna sosial melalui tindakan dan narasi. Pemerintah dan korporasi, misalnya, secara aktif memproduksi wacana bahwa eksploitasi sumber daya alam adalah bagian dari “kemajuan” dan “pembangunan berkelanjutan”. Narasi ini muncul dalam kebijakan publik, pidato resmi, maupun program CSR yang membingkai proyek eksploitasi sebagai kontribusi terhadap ekonomi hijau.
Objektivasi
Melalui media arus utama, narasi-narasi pembangunan itu kemudian memperoleh bentuk “kenyataan objektif” yang diterima masyarakat luas. Dalam kajian Rizki dan Wahyudi (2020), ditemukan bahwa media cenderung menampilkan perspektif negara dan korporasi secara dominan, sementara suara masyarakat adat atau komunitas terdampak jarang muncul. Narasi seperti “tambang sebagai berkah” atau “IKN sebagai solusi masa depan” menjadi bagian dari wacana dominan yang sulit digugat.
Internalisasi
Akhirnya, masyarakat menginternalisasi konstruksi ini sebagai kebenaran. Banyak orang menganggap bahwa kerusakan lingkungan adalah harga yang wajar untuk kemajuan, atau bahwa konflik lahan adalah konsekuensi pembangunan yang tak terhindarkan. Padahal, ini merupakan hasil dari proses konstruksi sosial yang menormalisasi ketimpangan dan ketidakadilan ekologis.
Peran Gen Z dalam Menciptakan Narasi Tandingan
Di tengah dominasi narasi lingkungan yang dibentuk oleh negara dan korporasi, masyarakat Indonesia, terutama generasi muda seperti Gen Z, semakin menyadari pentingnya menyuarakan perspektif alternatif. Gen Z, yang tumbuh di tengah kemajuan teknologi digital, memiliki literasi media yang tinggi dan kemampuan untuk memanfaatkan platform digital sebagai alat advokasi.
Jurnalisme warga (citizen journalism) menjadi salah satu cara paling efektif untuk menciptakan narasi tandingan terhadap konstruksi sosial dominan yang seringkali menutupi atau menyesatkan realitas ekologis. Dengan alat sederhana seperti ponsel, kamera, dan akun media sosial, masyarakat kini dapat mendokumentasikan perusakan lingkungan di sekitar mereka dan menyebarkannya secara luas, tanpa harus bergantung pada media arus utama.
Di sisi lain, jurnalisme warga juga menjadi ruang edukasi. Gen Z tidak hanya membuat konten yang bersifat reaktif, tapi juga informatif dan analitis, misalnya menjelaskan dampak tambang terhadap sumber air, atau mengulas kebijakan iklim pemerintah secara kritis. Hal ini menunjukkan bahwa narasi tandingan bukan hanya tentang melawan, tapi juga membangun pemahaman publik yang lebih utuh dan berkeadilan ekologis.
Dengan jangkauan digital yang luas dan semangat kolaboratif yang kuat, Gen Z memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak transformasi komunikasi lingkungan di Indonesia, dari narasi dominasi menuju narasi yang berkeadilan.
Penulis : Muhamad Fadhiil




















